Makanan sebagai Ruang Tamu Pengetahuan
Oleh: Afrizal Malna
Siapakah kita?
“Kita adalah apa yang kita makan.” Mungkin kita pernah mendengar ungkapan seperti ini, entah di mana.

Kalau kita melihat video performance Andy Warhol: “Eating a Hamburger” (channel DBTV Studios https://youtu.be/mWWuQJ_EIlc?si=oUBWWeKc9OvknVF8), video ini berdurasi mirip dengan komposisi musik John Cage “4’33” (1952) yang pernah heboh. Dalam video Andy Warhol, adegan makan hamburger merepresentasi kehidupan yang terisolasi oleh kesunyian; suara kertas bungkus hamburger terdengar nyaring dan sia-sia. Dalam komposisi John Cage yang berdurasi sama, berisi sebuah konser hening di depan piano, bahwa piano sama sekali tidak disentuh oleh pemain yang duduk diam di depannya selama 4 menit 33 detik, sehingga penonton seolah-olah bisa mendengar suara keheningan.
Andy Warhol duduk di sebuah meja yang bersih, membuka hamburger dari bungkusnya, dan di dalam bungkus itu masih ada sebuah kotak kardus yang melindungi hamburger dari dunia luar. Sebuah botol saos, dan Warhol mengenakan jas hitam dengan dasi. Makan jadi sebuah upacara untuk merayakan kesendirian, bukan untuk menikmati makanan; yang di makan adalah makanan siap saji dari industri makanan. Setelah selesai, semuanya menjadi sampah, diremas, dan siap dibuang ke tempat sampah.
Budaya makan Andy Warhol mulai banyak ditemukan di sekitar kita, terutama di kota-kota. Makanan siap saji yang dimakan karena kita tidak cukup banyak waktu, dalam pertumbuhan budaya urban kita menjadi makanan keluarga yang dianggap cukup memiliki gengsi. Pada libur akhir minggu, banyak keluarga memenuhi restoran-restoran siap saji ini, yang sebagian model pemesanannya sudah menggunakan komputer maupun online. Model pemesanan yang tidak hanya berfungsi mempercepat pelayanan, namun juga menambah nilai lebih bahwa restoran telah menggunakan teknologi canggih.
Namun, di sebuah kampung, kita masih bisa melihat seseorang makan dengan mengenakan sarung atau celana kolor, kaki diangkat ke kursi, dan mulai makan dengan lahap menggunakan lima jari tangannya, bahkan mulutnya memproduksi suara decak yang membuat cara makannya menjadi begitu ramai. Bau masakan (ikan asin, jengkol, atau bawang) masih bisa kita endus dari makanan yang dimakannya.
Hamburger yang dimakan Andy Warhol dan penampilannya memantulkan kultur urban, industri makanan, dan representasi penampilan seseorang sebagai bukan pekerja fisik. Sementara yang makan dengan angkat kaki, memantulkan kultur yang khas di mana makanan adalah tempat berkumpul banyak hal. Makanan sebagai ruang tamu untuk tempat bertemu. Budaya ngobrol di mana pun di sekitar kita, dan juga di warkop, tidak pernah lepas dari adanya makanan atau minuman. Berbagai tradisi yang kita jalankan, juga sesajen untuk roh leluhur atau keluarga kita yang telah meninggal, hampir selalu terkait dengan makanan yang disajikan sebagai persembahan dalam sesajen. Dari sebagian besar acara-acara yang kita buat, sebagian besar dana dianggarkan untuk makanan. Kita dilarang makan sambil berdiri atau berjalan. Dan syukurlah, belum ada larangan untuk merekam saat kita makan dengan video.
Sesungguhnya saya tidak pernah tertarik dengan makanan, walau orang tua saya hidup dalam usaha restoran Padang. Di restoran ini (yang sudah digusur tahun 70-an di daerah Kramat Senen, Jakarta Pusat), saya menikmati dua hal yang berbeda: orang bercengkrama sambil makan di restoran. Dan pekerja dapur yang memasak di tengah panasnya sekian banyak tungku api, kadang mereka memasak sambil bernyanyi dan bersenda-gurau. Sisa limbah masakan sering sangat menakutkan untuk saya. Di antaranya, kepala ayam, sisa-sisa tulang sapi, kambing, maupun tulang ikan.
Makanan untuk saya lebih terhubung dengan dua hal: lapar atau kenyang, dan kemudian menghasilkan sampah. Saya tidak pernah tertarik untuk memasak, walau ibu dan ayah saya melibatkan saya ke dalam aktivitas masak-memasak di rumah maupun di dapur restoran. Sebagai seseorang yang lahir dan besar dalam budaya urban di Jakarta, makanan juga tidak mendorong saya untuk melihatnya sebagai bagian dari gaya hidup. Saya mulai tertarik dengan makanan melalui isu sejarah rempah, dan saya pernah datang ke Ternate dan Tidore dalam sebuah pertemuan sastra tahun 2011. Melihat langsung perkebunan Pala, cengkih, berbagai situs sejarah, terutama Benteng, dan memantulkan sejarah kolonialisme di Indonesia berbasis perdagangan rempah.
Pengalaman ini mulai membuat saya tertarik melihat hubungan makanan dan sejarah. Tidak berbeda jauh dengan tokoh Maharani dalam cerpen “Kutukan Dapur”karya Eka Kurniawan. Sebelum Maharani mengunjungi museum cengkih, ia merupakan stereotip seorang istri yang didefinisikan melalui dapur dan ranjang. Hanya itu dunia yang dialaminya sehari-hari. Setelah mengunjungi museum, Maharani mulai mengenal tokoh-tokoh biologi seperti Alfred Russel Wallace, arkeolog Eugene Dubois, dan seorang perempuan bernama Diah Ayu yang ahli memasak. Diah dalam cerpen ini, digambarkan sebagai tokoh masa lalu yang banyak menginspirasi Maharani untuk membebaskan dirinya dari penjajahan suaminya. Ia mulai memiliki agenda untuk membunuh suaminya di meja makan melalui masakan yang ia buat sendiri.
Tahun 2013 terbit buku Sejarah Rempah: Dari Erotisme sampai Imperialisme karya Jack Turner (Komunitas Bambu), yang menggambarkan bagaimana rempah mengubah Nusantara dan juga dunia. Buku itu menjadi latar lahirnya puisi saya “Jembatan Rempah-Rempah” (dalam Museum Penghancur Dokumen, Yogyakarta, 2013). Buku yang terbit pada tahun yang sama dengan terbitnya buku Jack Turner:
Jembatan Rempah-Rempah
Adas manis · Akar wangi · Andaliman · Asam jawa · Asam kandis · Bangle · Bawang bombay · Bunga lawang · Bawang merah · Bawang putih · Cabe · Cengkeh · Cendana · Damar · Daun bawang · Daun pandan · Daun salam · Jembatan dari bumbu dapur ke darah Columbus · Gaharu · Gambir · Jahe · Jeruk limo · Jeruk nipis · Jeruk purut · Jintan · Kapulaga · Kayu manis · Kayu putih · Kayu mesoyi · Kecombrang · Kemenyan · Kemiri · Kenanga · Kencur · Kesumba · Ketumbar · Kopal · Kunyit · Lada · Jembatan dari parfum ke darah Vasco Da Gama Tabasco · Laurel · Lempuyang · Lengkuas · Mawar · Merica · Mustar · Pala · Pandan wangi · Secang · Selasih · Serai · Suji · Tarum · Temu giring · Temu hitam · Temu kunci · Temu lawak · Temu mangga · Temu putih · Temu putri · Temu rapet · Jembatan dari obat-obatan ke benteng perempuan berkalung mawar merah · Adas manis · Akar wangi · Andaliman · Asam jawa · Asam kandis · Bangle · Bunga lawang · Bawang putih · Cabe · Cengkeh · Cendana · Damar · Temu tis · Vanili · Wijen · Jembatan dari Diogo Lopes de Mesquita ke darah Ternate · Gaharu · Gambir · Jahe · Jeruk nipis · Jintan · Kapulaga · Kayu manis · Kayu putih · Kemenyan · Kemiri · Kenanga · Kencur · Kesumba · Ketumbar · Kunyit · Lada · Jembatan api yang terus mengirim kapal ke arsip-arsipmu.
Kemudian video art dari puisi yang sama pada channel youtube saya: “poet.box # rempah-rempah, yang dimiskinkan dan dikalahkan” (https://youtu.be/dYeRh9XoaoU).
Puisi rempah itu juga bagian awal saya mencoba melakukan pertemuan antara puisi dan arsip, dan menemukan metode yang lebih kompleks pada puisi saya Berlin Proposal (2015) kemudian Prometheus Pinball (2020).
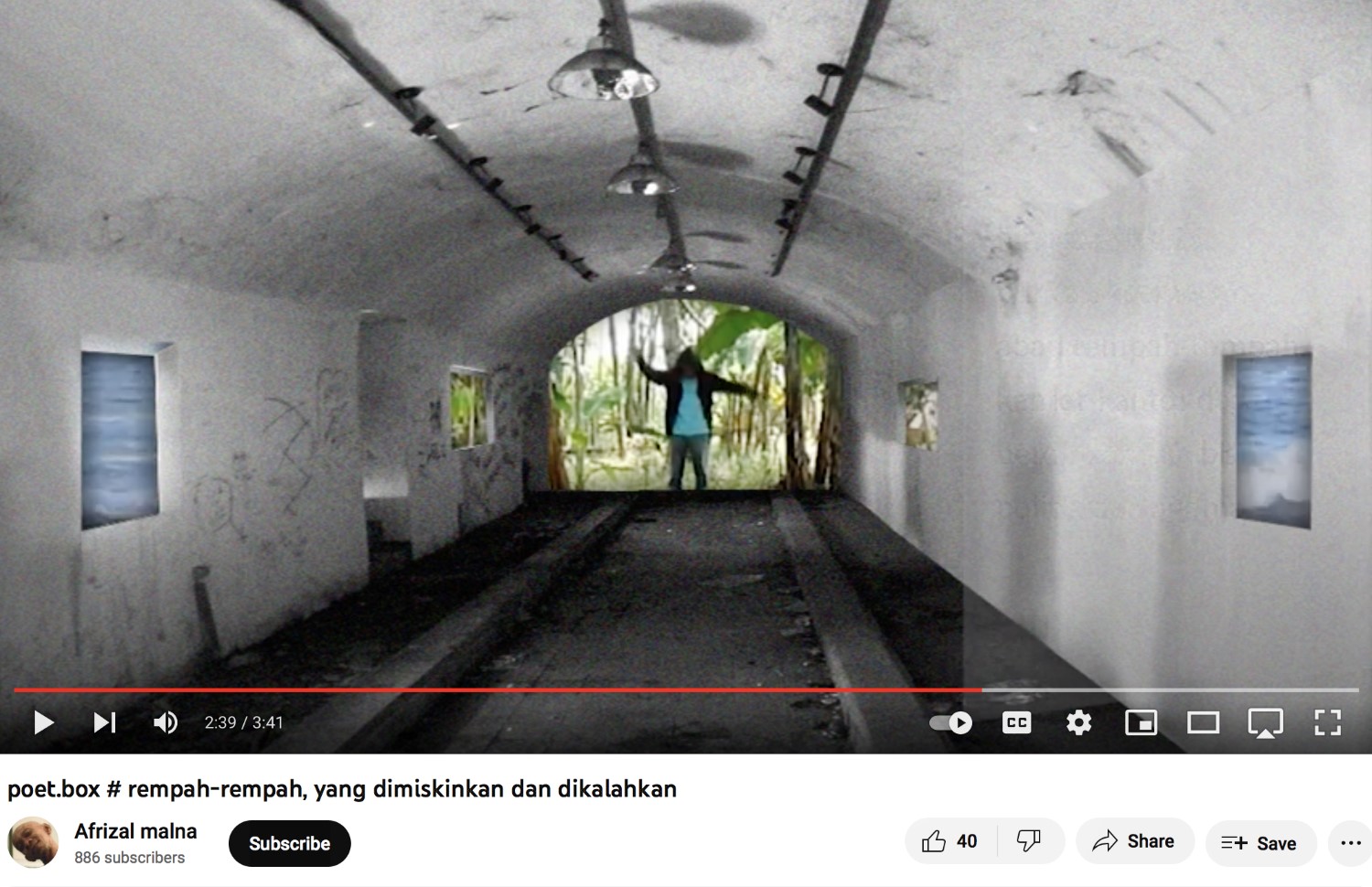
Makanan dan Perubahan Regenerasi Pengetahuan
Pengalaman kedua yang membuat saya lebih terbuka melihat makanan, terjadi setelah mengikuti workshop tari Topeng Losari oleh Nani Sawitri dalam salah satu program Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta untuk Lintas Media, tahun 2016. Dalam workshop itu, Nani menjelaskan, untuk menjadi penari Topeng Losari, penari harus puasa sekian tahap yang hampir seluruhnya terkait dengan makanan. Di antaranya puasa dan hanya makan nasi putih, makan nasi basi, makan cabai, dll. Metode ini menyadari saya bahwa seorang calon penari Topeng Losari perlu melakukan retreat, menjauh dari bentukan budaya melalui makanan. Retreat seperti ini juga kita temukan dalam tradisi Nyepi pada masyarakat Hindu, maupun sebagai salah satu tradisi Gereja. Makanan jadi efektif digunakan untuk banyak tujuan. Dalam sebuah percakapan dengan Sitor Situmorang, yang pernah berada dalam penjara Orde Baru selama 8 tahun (1967-1975), Sitor juga menceritakan pengalaman memakan nasi basi yang diberikan oleh petugas penjara.
Makanan dan rempah-rempah adalah titik sejarah paling penting yang mengubah kita semua secara global. Makanan membuat hubungan langsung antara tubuh kita dengan dunia di luar tubuh kita. Krisis pangan dan bencana kelaparan adalah menakutkan. Karena itu makanan adalah obat untuk kita hidup juga senjata untuk menguasai atau dikuasai.
Pada masa di mana makanan harus kita masak sendiri, dan bahan untuk makan harus kita cari sendiri, kita masih memiliki mekanisme regenerasi pengetahuan di sekitar tanaman maupun hewan yang kita makan dari generasi ke generasi. Tanpa pengetahuan ini, kita bisa mati, karena salah memilih tanaman beracun. Pabrik belum menyentuh budaya makan kita. Limbah makanan akan kembali ke tanah sebagai limbah organik. Masa yang membentuk tradisi yang panjang. Hampir pada banyak subkultur kita, ada kepercayaan di sekitar Dewi Kesuburan, seperti Dewi Sri di Jawa, untuk masyarakat agraris. Ada tradisi “Songkabala”, tolak bala untuk masyarakat nelayan Bugis, seperti di Takalar, Sulawesi Selatan, yang telah mengalami islamisasi. Setiap subkultur yang dibentuk oleh kondisi alam, membuat dramaturgi yang khas antara manusia, alam, dan makhluk-spiritual yang menentukan hasil alam untuk manusia. Kepercayaan yang lebih spesifik di mana makhluk-spiritual ini menghuni apa pun yang kita makan maupun kita gunakan dari alam, seperti dalam kepercayaan animis.
Dalam kepercayaan itu, apa yang kita makan, memiliki hubungan dengan dunia super-natural yang sering kita sebut sebagai “Sang Maha Pencipta”. Jadi makanan kita beririsan dengan spiritualitas. Dramaturgi ini tampak jelas dalam representasi tradisi nasi tumpeng.

Sumber: google.com
Kosmologi dalam bentuk gunung dalam tumpengan ini, menurut Jakob Sumardjo merepresentasi dunia atas (roh suci), dunia tengah (manusia), dan dunia bawah (negatif). Dalam wayang kulit juga ada gunungan yang mengawali pertunjukan. Kosmologi ini sangat jauh dibandingkan dengan bagaimana Copernikus memandang pusat tata surya. Pengetahuan lokal seolah-olah menarik konsep kosmologi ke dalam objek-objek paling dekat yang bisa dikenali, dialami, dan dimakan seperti cabe, bawang merah, telur ayam, maupun sirih. Objek-objek ini, oleh Jakob Sumardjo, dilihat sebagai representasi biner antara perempuan dan lelaki, bergantung dengan tujuan ritual yang dilakukan; atau sebagai representasi di sekitar konsep “kosong dalam isi”. Jakob memahami konsep ini sebagai lenyapnya dualitas subyek dan obyek. Merujuk pada pengalaman dan perasaan makna yang bukan ini yang bukan itu, sesuatu yang teralami adanya tetapi tak terumuskan apanya.
Objek-objek itu merupakan identitas utama sebagai visualisasi dari bagaimana pengetahuan lokal menghadirkan konsep kosmologinya sebagai asal-usul yang terdekat. Dalam perut cabe ada rongga, seperti rahim untuk benih atau bibit-bibit baru. Cabe dan benih-benih itu merupakan siklus berulang yang mengawali dan mengakhiri kehidupan. Dalam belahan bawang merah, ada lingkaran luar dan lebih ke dalam menuju titik kematangan, seperti siklus waktu dalam kualitasnya dan bukan kuantitasnya. Begitu juga telur dalam lingkaran putih dan kuning di dalamnya sebagai biner antara yang harus lahir dengan yang menyiapkan serta melindungi benih di dalamnya sebagai calon kehidupan baru.

Walter Spies, “Dream landscape”, 1927.
Dalam lukisan Walter Spies yang dibuat di Bali, 1927 (“Dream Landscape”), kosmologi atau dramaturgi segitiga itu tampak pada sosok lelaki tua yang menembus tiga lapisan alam, sebagai representasi antropomorfisme yang hierarkis, seperti tumpeng.
Siapakah yang menjadi pusat reproduksi pengetahuan lokal itu? Ketika posisi perempuan mulai dibatasi dari kehidupan publik, dan mengalami domesitifikasi, perempuan berada dalam rutin keseharian di dapur maupun di rumah, maka reproduksi pengetahuan itu dijalankan oleh perempuan. Risa Permanadeli menyebutnya sebagai common sense. Dan medan pengetahuan ini ada pada perempuan dan di desa sebagai pengetahuan lokal. Dalam pertunjukan Waktu Batu #4: Rumah yang Terbakar Teater Garasi di TIM, Jakarta, 2023 pada forum Djakarta International Teater Platform, adegan Dewi Sumbi yang memukul anaknya, yang telah membunuh ayahnya sendiri, menggunakan centong untuk masak yang khas perempuan. Bukan dengan senjata yang bisa mematikan seperti yang dilakukan lelaki.
Dalam pertunjukan itu juga dikutip analisa Silvia Federici: “Sebelum munculnya kapitalisme, perempuan memainkan peran utama dalam produksi pertanian. Mereka mempunyai akses terhadap tanah, penggunaan sumber daya dan kendali atas tanaman yang mereka tanam, yang semuanya menjamin otonomi dan kemandirian ekonomi mereka dari laki-laki. Di Afrika, mereka memiliki sistem pertanian dan penanaman, yang merupakan sumber budaya perempuan tertentu, dan mereka bertanggung jawab atas pemilihan benih, sebuah operasi yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pengetahuannya disebarkan melalui generasi. Hal serupa juga terjadi pada peran perempuan di Asia dan Amerika. Di Eropa juga, hingga akhir periode abad pertengahan, perempuan mempunyai hak penggunaan lahan dan penggunaan “milik bersama” —kayu, kolam, lahan penggembalaan— yang merupakan sumber penghidupan yang penting. Selain bertani dengan laki-laki, mereka juga memiliki kebun tempat mereka menanam sayur-sayuran serta tanaman obat.”

Pertunjukan Teater Garasi: “Waktu Batu #4 - Rumah yang Terbakar”, ARTJOG 2023, Yogyakarta (dok. Erwin Octavianto)
Rempah-Rempah yang Mengubah
Akhir Abad Pertengahan, juga merupakan transisi menjelang berakhirnya abad keemasan rempah-rempah. Era yang pernah penopang kerajaan-kerajaan besar dari Sriwijaya hingga Majapahit. Rempah-rempahlah yang membuat tradisi gastronomi kita menjadi laboratorium keberagaman. Rempah-rempah tidak hanya membawa kita ke era kolonialisme, menerima berbagai pengaruh dari China, India, Eropa, kemudian ditutup pada era pendudukan Jepang, dan juga Islamisasi. Hubungan kita dengan Portugis tidak semata-mata terkait dengan rempah-rempah. Di balik perdagangan rempah-rempah, Portugis juga membawa barang-barang berharga yang mereka jual, seperti kain dari Gujarat, Benggala, Koromandel. Juga beras dari para pedagang Jawa.
Rempah-rempah menopang kehidupan kita yang digunakan dari kebutuhan ritual, obat-obatan, makanan, parfum hingga berubahnya sejarah seks. Perkembangan transportasi maritim, terbentuknya peta dengan kartografi yang lebih detail (Jan Huygen van Linschoten), geografi (Claudius Ptolemeus), karya botanikal (Rumphius dan kemudian Alfred Russel Wallace yang menginspirasi Darwin), serta pertumpahan darah yang panjang karena perebutan wilayah perdagangan yang berpusat pada rempah-rempah. Sejak mengenal cengkeh, orang-orang di istana Tiongkok memiliki kebiasaan menyelipkan cengkih dalam mulut, yang membuat napas mereka harum ketika berbicara di hadapan Kaisar Han. Hingga akhirnya era keemasan rempah-rempah berakhir. Tahun 1776 merupakan panen pertama di mana cengkih mulai ditanamkan di koloni Prancis, disalurkan dari Mauritius menuju Madagaskar, Pemba, dan Zanzibar dan tumbuh subur. Ini merupakan hasil kerja seorang spionase Prancis, Pierre Poivre, yang menyelusup ke Maluku ketika kawasan ini masih berada dalam hegemoni VOC.
Seorang petani memetik Pala di perkebunan Pala, Ternate, 2011. Foto Afrizal Malna
Rawon dan Rendang, merupakan salah satu kreasi masakan kita yang populer. Dan menjadi cukup kompleks ketika jadi bagian dari politik identitas dengan otoritas agama di dalamnya. Kasus “Rendang Babi” yang pernah viral pada masa pandemi Covid-19, dan mendapat reaksi dari beberapa tokoh Minang, merupakan representasi dari makanan sebagai identitas dan kepercayaan.
Makanan dan Sampah
Rempah-rempah mengubah kita dari makanan, obat-obatan, parfum, pertemuan antarbudaya, politik identitas, dan relasi kuasa. Latar utama terjadinya kolonialisme dan kemudian modernisme. Rempah membuat makanan sebagai ruang tamu untuk pengetahuan dan sejarah, di mana hampir semua elemen identitas saling membaur dan bercampur. Dalam sebuah percakapan dengan seorang penyair dari Makassar, M. Luthfi Pradana Al-Ghifajri, mengungkapkan cara tradisi Bugis mempersilakan tamunya untuk makan dengan ungkapan: “Sila mencicipi obat-obatan ini”. Makanan sebagai obat-obatan. Dalam tradisi Jawa ada doa dalam bentuk mantra:
tamba teka lara lunga
cacing kremi padha mati
kari siji
nggo tunggu waras
Obat diminum, penyakit pergi, cacing kremi pada mati. Namun sisakan satu cacing kremi untuk menjaga kesehatan kita. Mantra yang memperlihatkan wawasan mikrobiologi bahwa ada banyak mahluk lain yang hidup di dalam dan bersama tubuh kita. Mahluk-mahluk yang bisa saling membunuh atau menopang kehidupan bersama. Tubuh sebagai super-organisme dikaitkan sebagai ekosistem bersama dengan mahluk-mahluk kecil lainnya yang hidup dalam tubuh kita. Makanan dalam tradisi ritual, juga merepresentasi bahwa yang kita makan jadi bagian dari makanan spiritual. Antara lain meliputi bubur merah, bubur putih, ayam ingkung, sega golong, juga sirih.
Kapitalisasi dalam industri makanan telah menggeser makanan dari rumah ke pabrik. Dan ikut menggeser posisi perempuan dan desa. Dalam Festival Performa Kaliwungu, di Kampung Pakuwojo, Kaliwungu, Jawa Tengah, saya sempat melihat tradisi yang mengaitkan peran perempuan dalam konteks makanan. Yang pertama tradisi Kupat Sumpil yang telah mengalami Islamisasi. Tradisi ini berlangsung dalam acara-acara peringatan agama, dan menggunakan Kupat Sumpil sebagai makanan khas di Kaliwungu yang dibuat oleh ibu-ibu di desa, dan jadi subyek utama performance Syska La Veggie dalam festival itu. Tetapi dalam tradisi kedua, yang berlangsung sebulan sekali di hari Jumat, perempuan (terutama ibu-ibu) melakukan saling-tukar makanan. Suasana begitu ramai saling tukar dan saling ngobrol. Makanan yang ditukar merupakan hasil masakan di rumah dan makanan pabrik yang dibeli di pasar. Sebagian besar warung yang berada di Kampung Pakuwojo ini juga lebih banyak menjual makanan pabrik, terutama minuman dalam kemasan plastik.
Kapitalisasi makanan ini tampak provokatif dalam salah satu karya Entang Wiharso, yang disebut Ilham Khoiri sebagai “teater kekerasan”:

Entang Wiharso: instalasi “feast table,”. Foto: by ilham khoiri (https://ilhamkhoiri.wordpress.com/2011/01/04/teater-kekerasan-entang-wiharso/)
Instalasi Entang itu memperlihatkan motif ikan yang juga menjadi motif yang sama pada sosok dua tubuh manusia yang menghadapinya. Karya yang memantulkan pesan bahwa mengambil terlalu banyak dari alam sama dengan kita memakan diri sendiri. Kapitalisasi makanan ini pada gilirannya mengubah makanan menjadi sampah, dan berkontribusi besar dalam pencemaran lingkungan:

Krisis global, seperti laporan World Resources Institute di atas, sebagai efek antroposen dari aktivitas produksi manusia yang memproduksi jutaan ton sampah plastik, sampah elektronik, dan sampah sisa makanan setiap tahun. Ini memantulkan kembali bagaimana pengetahuan lokal memosisikan alam sebagai biosentris, dan terepresentasi melalui tradisi makanan lokal yang membuat hubungan antara makanan, alam, spiritualitas, obat-obatan, dan kembali ke alam sebagai sampah organik.
Makanan yang sebelumnya kita lihat sebagai ruang tamu untuk pengetahuan dan sejarah, tempat terjadinya regenerasi pengetahuan, kini menjadi ruang tamu untuk sampah. Pandemi Covid-19, membuat lebih banyak lagi produsen makanan yang menggunakan plastik sebagai kemasan. Bahkan restoran yang biasa menggunakan piring maupun gelas dari kaca, kini menggunakan plastik maupun styrofoam untuk sajian dingin maupun panas. Menyerahkan apa yang kita makan dan kita masak sendiri kepada pihak lain, yaitu pabrik, sama dengan memberikan sumber-sumber pengetahuan kita, kedaulatan, dan identitas kita kepada pihak lain yang akan menguasai kita.

Performance Syska La Veggie “Kupat Sumpil” dalam Festival Performa Kaliwungu, 2023. Foto: Afrizal Malna
Di balik bergesernya pembuatan makanan dari rumah ke pabrik, karena kapitalisme, memantulkan pertanyaan apakah cerpen Eka Kurniawan (“Kutukan Dapur”) berubah menjadi (“Kutukan Pasar”) sebagai perumpamaan dari perubahan ini, membuat peran perempuan kian terbuka dan melebar ke ruang publik. Dari pengalaman menyaksikan performance Syska La Veggie tentang Kupat Sumpil di Kampung Pakurejo dalam Festival Performa Kaliwungu (yang diprakarsai oleh Haryo Utomo), 17 September 2023, ibu-ibu yang memasak Kupat Sumpil, ternyata tidak pernah masak bersama tentang jenis makanan ini. Ketika mereka melakukan masak bersama di ruang terbuka melalui performance itu, mereka jadi bisa saling melihat perbedaan memasak kupat dari menggunakan daun bambu, pembuatan sambal dari parutan kelapa, hingga bentuk piring dari daun pisang, ternyata terdapat beberapa perbedaan di antara mereka. Dan dalam performance ini, mereka jadi saling berbagi pengetahuan di sekitar masakan Kupat Sumpil. Terutama untuk generasi muda yang sudah tidak mengenal cara memasak makanan lokal ini.
Berubahnya tradisi memasak, dari dapur ke kafe-kafe maupun pabrik, ikut mengubah ruang tamu kita dari rumah ke pasar (warung, restoran, kafe). Program masak bersama, yang lebih bersifat lintas generasi dengan keberagaman gender, mungkin membuat kita menemukan ruang tamu baru yang lebih dinamis, mengenali kembali tradisi memasak sebagai bagaimana kita melihat arah budaya yang lebih sesuai dengan ekosistem kita.***
(Makalah ini ditulis sebagai materi Wicara Peristiwa Sastra Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023).